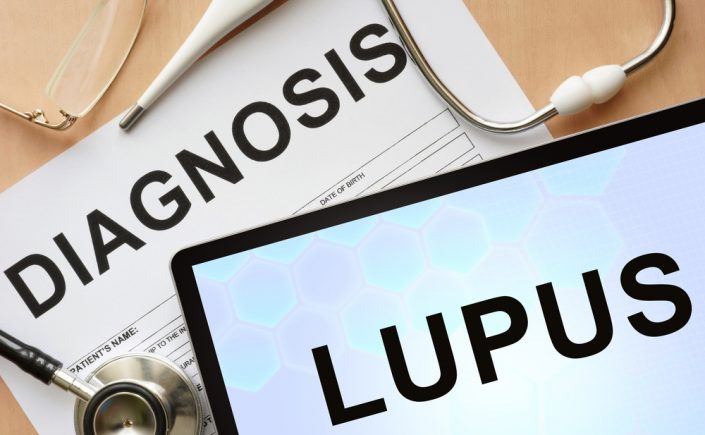Studi, “Terapi Sel T Regulator Adoptif pada Pasien dengan Sistemik Lupus Erythematosus,” diterbitkan dalam jurnal Arthritis & Rheumatism meneliti tentang Regulatory T-cells.
Regulatory T-cells (Tregs) adalah anggota dari sistem kekebalan yang secara alami menekan sel-sel kekebalan tubuh lain dan bisa menjadi pengobatan yang efektif untuk penyakit autoimun.
Pendekatan yang efektif untuk meningkatkan jumlah Treg adalah transplantasi. Ini adalah suatu proses di mana sel dikumpulkan dari darah pasien, diperluas di laboratorium hingga beberapa juta, dan disuntikkan kembali ke pasien.
Tetapi penelitian sampai saat ini telah meneliti efek dari transplantasi Treg hanya dalam darah.
Dalam upaya untuk mempelajari transplantasi Treg pada pasien lupus eritematosus sistemik, para peneliti mengembangkan uji klinis Fase 1 (NCT02428309). Tujuan transpalasi ini untuk mendaftarkan sembilan pasien dengan manifestasi kulit saja.
“Alasan asli untuk fokus pada pasien dengan lupus kulit adalah aksesibilitas biopsi kulit untuk menilai peradangan, dibandingkan dengan jaringan lain seperti ginjal, yang jauh lebih sulit diperoleh,” tulis para peneliti.
Namun, karena alasan logistik – terutama karena pasien dengan lesi kulit sering memiliki komplikasi lain yang lebih parah. Peneliti hanya dapat merekrut satu pasien, seorang wanita Afrika Amerika berusia 46 tahun, ke dalam persidangan.
Treg wanita secara efektif diekstraksi dan diperluas di laboratorium. Ini terbukti karena sel-sel tersebut cenderung langka dan cacat pada pasien lupus.
Para peneliti tidak melihat hasil yang signifikan mengenai keadaan keseluruhan lesi kulit, dan sel yang ditransplantasikan menghilang dari darah empat minggu setelahnya.
Namun, para peneliti menemukan hasil yang menarik ketika mereka mengukur respon imun di kulit. Bahkan, 12 minggu setelah transplantasi, jumlah Treg kulit hampir dua kali lipat. Treg aktif juga meningkat lima kali lipat.
Ini menunjukkan bahwa Treg tetap berfungsi dan terlokalisasi pada jaringan yang meradang.
interferon gamma pemicu respon imun
Selain itu, tingkat interferon gamma, sebuah molekul yang bertindak sebagai pemicu respon imun, menurun secara signifikan setelah transplantasi. Sementara itu, interleukin-17 (IL-17) molekul inflamasi dengan sifat protektif sangat meningkat.
Untuk memvalidasi hasil mereka, para peneliti menguji efek transplantasi Treg dalam model tikus untuk peradangan kulit. Hasilnya serupa, dengan tikus menunjukkan pergeseran dari sel penghasil interferon ke sel IL-17-positif.
“Bersama-sama, hasil ini menunjukkan bahwa terapi Treg dapat mengubah keseimbangan subset [T-sel] di situs lokal yang meradang, yang mungkin memiliki efek pada manifestasi klinis penyakit,” para peneliti menyimpulkan.
Hasil awal ini perlu divalidasi lebih lanjut pada lebih banyak pasien. Tetapi mereka menunjukkan bahwa transplantasi Treg dapat membantu mengurangi peradangan pada organ yang terkena penyakit autoimun seperti lupus.